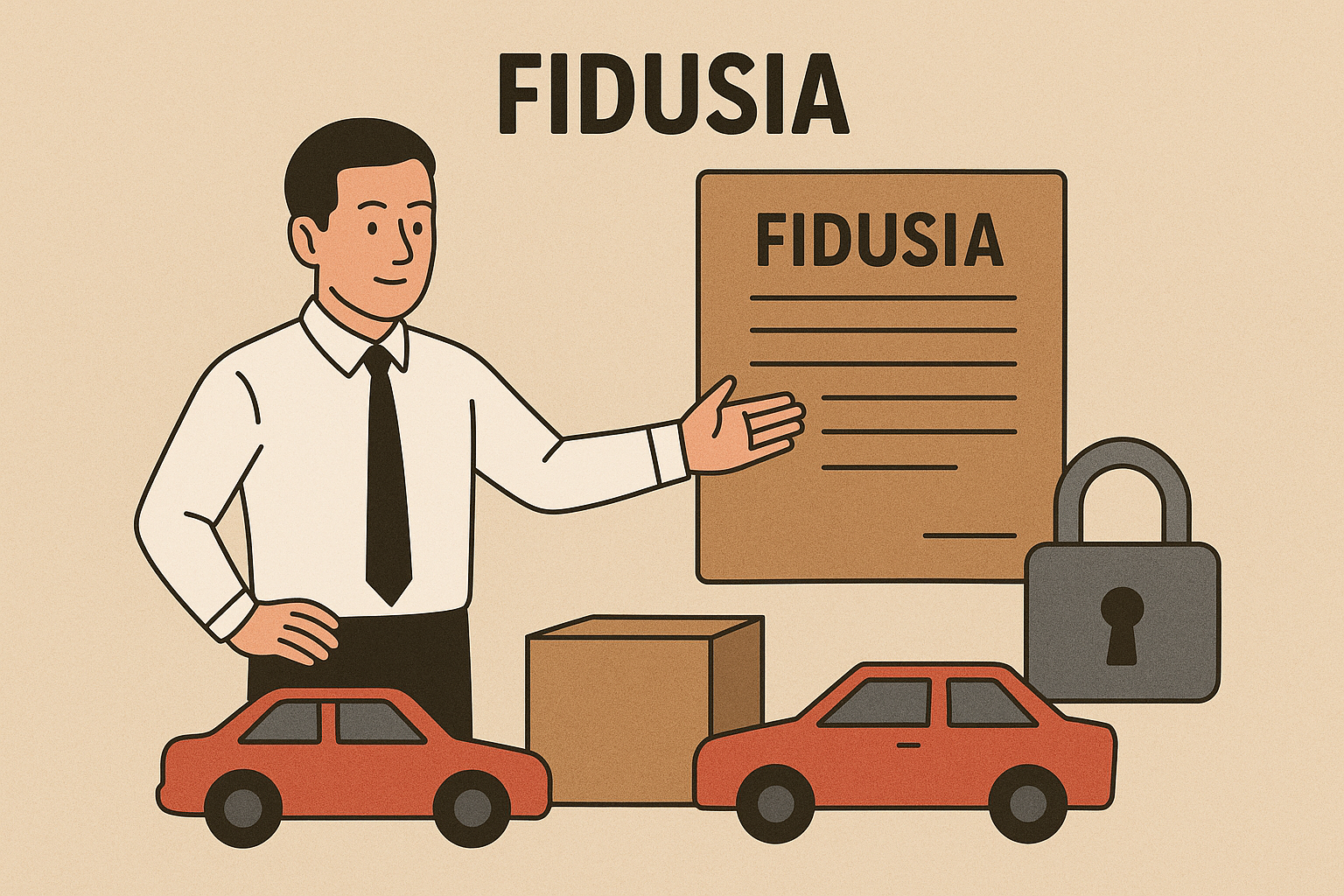Hukum Fidusia
Dasar hukum fidusia itu ibarat kitab sucinya dunia pembiayaan tanpa itu, penarikan kendaraan bisa berubah jadi debat panjang yang bikin warga sekampung ikut jadi komentator. Fondasinya adalah UU No. 42 Tahun 1999 ( tentang jaminan fidusia ), yang menurut pakar hukum seperti Prof. J. Satrio, menjadi pagar kokoh agar hubungan kreditur–debitur tidak berubah seperti drama rebutan remote TV. Ditambah Putusan MK 18/2019 yang bikin eksekusi harus lebih sopan dan beretika, serta aturan pendaftaran elektronik ala Kemenkumham yang membuat fidusia kini serba digital. Semua ini berjalan berdampingan dengan asas perjanjian dalam KUHPerdata, sehingga hukum fidusia tetap rapi, tertib, dan tidak asal comot.
Syarat terjadinya jaminan fidusia itu mirip resep rendang: kalau satu bumbu hilang, hasilnya cuma daging biasa, bukan rendang juara. Pertama harus ada perjanjian pokok, ibarat kompor yang menyalakan hubungan utang-piutang. Lalu dibuat Akte Fidusia di hadapan notaris kata pakar hukum Prof. Ridwan Khairandy, akta ini bukan sekadar kertas, tapi tiket resmi menuju kekuatan eksekusi. Isinya lengkap: identitas, nilai objek, sampai syarat perjanjian. Terakhir, semuanya harus didaftrar elektronik ke Kemenkumham sampai keluar sertifikat fidusia. Tanpa pendaftaran? Sama saja seperti masak tanpa garam, hubungannya ada, tapi tidak punya “gigi” untuk eksekusi.
Jaminan fidusia itu punya tanggal tamat layaknya kartu garansi, dan UU 42/1999 Pasal 25 sudah menuliskannya dengan rapi. Menurut pakar hukum seperti Prof. Yahya Harahap, fidusia akan gugur secara manis begitu utang pokok lunas, seperti ending drama yang akhirnya bahagia. Bisa juga berakhir karena penerima fidusia melepaskan haknya, biasanya setelah semua urusan administrasi beres dan tidak ada utang buditersisa. Atau karena objeknya musnah, entah hilang, terbakar, atau mengalami total loss, meski musnahnya barang tidak otomatis memusnahkan utangnya. Intinya, fidusia itu bukan cinta abadi; ada saat mulai, dan ada saat resmi pamit.
Jaminan fidusia bisa batal kalau syarat utamanya melenceng, mirip acara kawinan yang gagal gara-gara pengantinnya salah venue. Menurut pakar hukum seperti Prof. J. Satrio, fidusia itu wajib hukumnya memenuhi prosedur formal, kalau akta sudah dibuat tapi tidak didaftarkan, statusnya langsung turun derajat jadi hubungan perdata biasa, alias nggak punya taring eksekusi. Kalau perjanjian pokoknya tidak sah, fidusianya ikut tumbang seperti domino. Dan kalau barang yang dijaminkan ternyata sudah dipindahtangankan, ya jelas batal, masa menjaminkan barang yang secara hukum bukan miliknya lagi? Itu sih ibarat ngasih kado tapi kadonya numpang.
Hapusnya fidusia itu mirip momen closing ceremony dalam hubungan utang-piutang. Menurut pakar hukum seperti Prof. Herlien Budiono, fidusia resmi pamit ketika utang lunas, penerima fidusia melepas haknya, atau objek jaminannya musnah, entah tenggelam, terbakar, atau lenyap seperti sandal jemaah masjid. Bahkan putusan pengadilan juga bisa menghapusnya. Setelah itu, pihak kreditur wajib mengurus roya di sistem Kemenkumham, biar jejak administrasinya bersih dan tidak jadi “mantan yang masih nyangkut di data.”
Eksekusi objek fidusia itu ibarat panggung drama hukum yang tak pernah sepi penonton. Menurut Prof. Ridwan Khairandy, kunci utamanya jelas: penarikan hanya boleh dilakukan jika ada wanprestasi yang disepakati, didukung sertifikat fidusia, dan mengikuti rambu putusan MK 18/2019. Tapi di lapangan, ceritanya sering lain, mulai dari penarikan tengah malam ala film action sampai nasabah yang tiba-tiba berubah jadi ninja, ngumpet di balik pintu. Prosedurnya harus rapi, manusiawi, dan berbasis bukti, bukan sekadar aksi dadakan yang bikin satu RT jadi saksi.
Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam fidusia itu sering bikin bingung, padahal menurut pakar hukum Prof. Subekti, keduanya seperti dua jalur tol yang beda gerbangnya. Wanprestasi muncul ketika nasabah mangkir dari kewajibannya, telat bayar, pura-pura lupa, atau tiba-tiba hilang sinyal. Sementara PMH terjadi kalau ada tindakan yang melanggar hak orang lain, misalnya debt collector main ancam, atau nasabah sengaja menyembunyikan kendaraan. Menariknya, kedua pihak bisa saling serang balik secara hukum: nasabah bisa menggugat DC yang kelewatan, dan leasing bisa memproses pidana kalau unit dipindah tangan. Intinya, fidusia punya aturan jelas; yang ngawur biasanya justru perilaku manusianya.
Penyalahgunaan debt collector itu topik panas yang sering bikin warga satu kompleks mendadak jadi ahli hukum dadakan. Menurut pakar seperti Prof. Muladi, DC tidak boleh mengancam, mengintimidasi, apalagi berlagak seperti preman pensiun, langsung bisa masuk ranah pidana jika melampaui batas. POJK juga sudah menetapkan standar etik: sopan, terlatih, dan wajib tersertifikasi, bukan yang dipilih karena suaranya paling lantang. Jika DC melanggar SOP, nasabah punya hak melapor, dan leasing bisa kena imbas hukum. Jadi, penagihan itu tugas profesional, bukan ajang pamer otot.
Kedudukan sertifikat jaminan fidusia itu sering bikin penasaran, karena kekuatannya disebut setara titel eksekutorial, mirip putusan pengadilan yang sudah ketok palu. Menurut pakar hukum Prof. J. Satrio, sertifikat fidusia memberi hak langsung mengeksekusi tanpa lewat drama persidangan, asal syaratnya lengkap dan terdaftar sah di Kemenkumham. Namun, problem muncul ketika ada sertifikat palsu, pendaftaran asal-asalan, atau kebingungan antara versi fisik dan elektronik. Di sinilah diskusi menghangat: sertifikatnya memang kuat, tapi prosesnya harus benar, bukan seperti beli stempel di pinggir jalan.
Dualisme hukum antara Putusan MK dan UU Fidusia itu ibarat dua lampu lalu lintas yang menyala bersamaan merah dan hijau, bikin bingung siapa pun di jalan. Menurut Prof. Ridwan Khairandy, putusan MK menuntut eksekusi yang lebih manusiawi dan berbasis kesepakatan wanprestasi, sementara UU Fidusia masih memberi kekuatan eksekutorial penuh pada sertifikat. Alhasil, leasing sering terjebak legal gap yang membingungkan: boleh tarik atau tidak? Situasi ini jadi bahan skripsi favorit karena penuh drama, debat intelektual, dan ruang interpretasi yang luas.
Tindakan melawan hukum oleh nasabah dalam fidusia ini sering jadi “plot twist” paling seru, mulai dari memindahtangankan motor sebelum lunas, menyembunyikan unit di rumah mertua, sampai mengganti nomor rangka layaknya agen rahasia. Padahal, menurut Pasal 372–374 KUHP, tindakan seperti itu bisa masuk kategori penggelapan, serius, bukan sekadar akalin leasing. Banyak nasabah berpikir bisa kabur dari kewajiban, padahal hukum jalan lebih cepat daripada sinyal WiFi. Di mata ahli hukum Indonesia, perilaku ini bukan hanya wanprestasi, tapi juga bisa menyeret pelaku ke ranah pidana jika terbukti ada niat mengaburkan atau menghilangkan objek fidusia.
Eksekusi suka rela yang humanis itu ibarat “ngobrol baik-baik sebelum minta kembali barang tetangga” nggak bisa pakai nada komando ala film koboi. Dunia leasing modern kini mengutamakan komunikasi efektif: duduk bareng, jelasin kondisi, dan cari jalan tengah tanpa bikin jantung nasabah deg-degan. Pendekatan win-win jadi kunci, karena keduanya ingin masalah selesai tanpa drama. Biasanya diakhiri dengan *pernyataan kesepakatan* yang ditandatangani secara sadar dan tanpa tekanan, sehingga prosesnya terasa lebih etis, modern, dan jauh dari kesan “asal tarik”.
Fidusia digital itu ibarat ngurus jaminan lewat HP sambil rebahan, praktis tapi tetap punya jebakan Batman. Dengan pendaftaran elektronik dan integrasi data OJK Kemenkumham, prosesnya makin cepat, rapi, dan tidak bikin kening berlipat seperti ngurus berkas zaman fotokopi lima rangkap. Tapi di balik kemudahan itu ada risiko pemalsuan digital yang bisa muncul seenak meme tengah malam. Karena itu, para pakar hukum mengingatkan: teknologi memang mempercepat, tapi kehati-hatian tetap wajib, jangan sampai dokumen digital lebih licin dari belut yang baru disabuni.
Fidusia itu ibarat jaminan kekinian yang fleksibel, beda dengan gadai yang harus diserahkan barangnya, mirip titip motor ke abang parkir tapi versi legal. Hipotik dan hak tanggungan cocok untuk barang besar seperti kapal dan tanah, yang prosesnya lumayan panjang seperti antre bakso saat hujan. Sementara leasing syariah punya aturan sendiri yang lebih adem, karena menghindari bunga dan pakai akad-akad yang bikin hati tenang. Dibanding semuanya, fidusia menawarkan kemudahan tanpa harus melepas barang dari tangan, sehingga banyak dipilih karena praktis, luwes, dan tidak ribet seperti jaminan generasi lama.
Fidusia sebagai jembatan ideal antara kreditur dan debitur: fleksibel, efisien, namun tetap mengandung unsur kehati-hatian agar tidak merugikan kedua belah pihak. – Prof. Dr. Ahmad Ubbe
Horas Hubanta Haganupan.
Horas …Horas … Horas