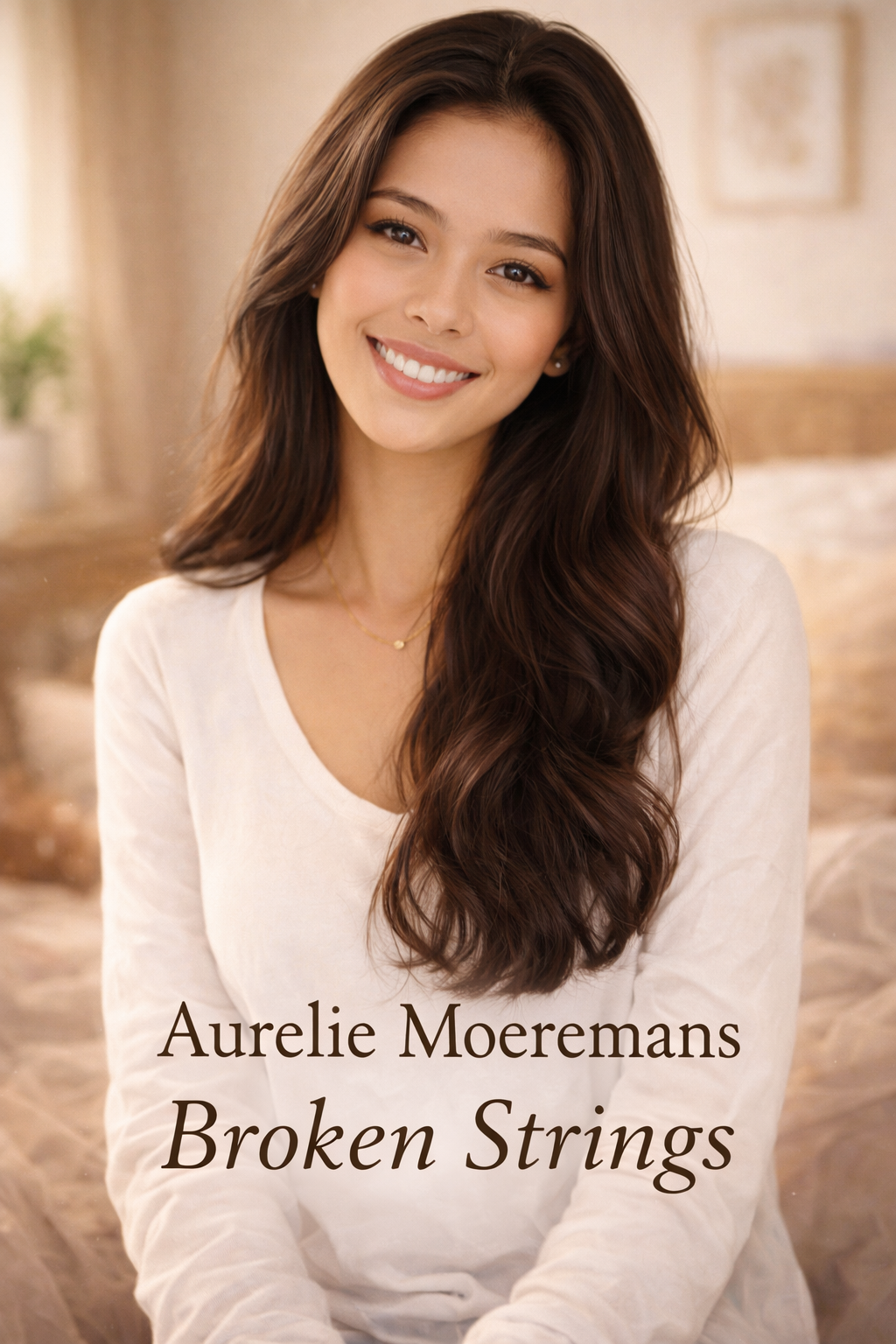Siapa Aurelie Moeremans?
Jadikabar.com – Publik mengenalnya sebagai wajah yang rapi di layar: aktris, model, penyanyi, figur publik dengan senyum yang terlatih. Darah Belgia mengalir dalam tubuhnya, tapi hidupnya tumbuh dalam lanskap hiburan Indonesia yang keras dan penuh tuntutan. Kariernya dimulai sejak usia muda, ketika pujian datang lebih cepat daripada kesiapan batin untuk menolaknya. Dunia menyebutnya sukses. Padahal, seperti banyak kisah lain, kesuksesan sering kali hanya tampak utuh dari kejauhan.
Di balik sorotan itu, Aurelie menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata: relasi toksik, manipulasi emosional, kekerasan psikologis yang tidak meninggalkan memar. Ia tidak dipukul, tidak diseret, tidak berdarah. Namun jiwanya terkikis perlahan. Psikologi punya istilah untuk itu: gaslighting, trauma bonding. Masyarakat kita punya istilah lain yang lebih singkat dan sering menyakitkan: drama.
Masalahnya, luka batin memang tidak pandai berteriak. Ia bekerja diam-diam. Membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Membiasakan rasa bersalah. Mengajari korban untuk diam, demi terlihat kuat.
Mengapa Aurelie menulis buku?
Karena diam terlalu lama sering berubah menjadi penjara.
Broken Strings bukan novel. Ia memoar—pengakuan. Judulnya sederhana, tapi tepat: senar yang putus. Dunia hiburan menyukai musiknya, tak peduli bagaimana kondisi senarnya. Selama bunyi masih keluar, pertunjukan harus jalan. Dalam buku itu, Aurelie mengambil kembali kendali atas ceritanya sendiri. Dalam psikologi trauma, ini dikenal sebagai narrative healing: penyembuhan lewat penceritaan ulang, ketika korban menjadi pemilik narasi, bukan sekadar objek kisah.
Menulis, dalam konteks ini, bukan membuka aib. Ia justru menutup lingkaran kekerasan agar tidak diwariskan. Ia berkata—tanpa teriak—bahwa luka emosional itu nyata. Dan bahwa popularitas tidak memberi kekebalan apa pun terhadap trauma.
Kisah Aurelie bukan pengecualian. Ia berdiri dalam antrean panjang figur publik dunia: Britney Spears, Amanda Bynes, Michael Jackson, Oprah Winfrey. Berbeda latar, serupa pola. Sistem memuja hasil, citra, dan ketahanan, sambil menyingkirkan kesehatan jiwa sebagai urusan pribadi.
Pertanyaannya lalu bergeser: jika figur publik saja bisa runtuh, bagaimana dengan mereka yang tak punya panggung?
Di sinilah negara seharusnya hadir. Namun sering kali ia datang terlambat.
Negara, Pendidikan, dan Luka yang Tidak Masuk Kurikulum
Negara hadir melalui sekolah. Melalui kurikulum. Melalui buku pelajaran dan ruang kelas. Tapi di ruang-ruang itu, anak-anak lebih sering diajari menghafal daripada mengenali emosi. Mereka diajari bersaing, bukan berempati. Diajar untuk tahan banting, bukan mengenali batas.
Pendidikan kita gemar berbicara tentang karakter, tapi gagap ketika harus membahas trauma. Kesehatan mental masih dianggap tambahan, bukan fondasi. Kekerasan emosional jarang disebut dengan namanya. Ia tidak diujikan. Tidak masuk rapor. Padahal justru di usia sekolah, banyak luka pertama terbentuk: perundungan, manipulasi, relasi tidak setara, tekanan prestasi, dan kekerasan verbal yang dinormalisasi.
Sekolah sering menjadi tempat anak belajar diam. Bukan karena mereka kuat, tapi karena tidak tahu ke mana harus mengadu.
Di sinilah ironi itu muncul: negara punya Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi pendidikan belum sepenuhnya melatih anak mengenali bahwa dirinya layak dilindungi. Negara bicara hak, tapi belum cukup mengajarkan bahasa luka.
Lalu kita bertanya: apakah produk pendidikan kita sedang membentuk manusia utuh, atau hanya melatih mereka agar tampak baik-baik saja?
Komnas Perlindungan Anak: Hadir atau Sekadar Ada?
Komnas Perlindungan Anak dibentuk sebagai pengakuan bahwa anak bukan milik keluarga semata. Ia subjek hukum, subjek kemanusiaan. Namun dalam praktik, lembaga ini sering terjebak dalam pola reaktif. Ia hadir setelah kasus meledak. Setelah kerusakan terjadi. Setelah luka terlanjur dalam.
Perlindungan anak seharusnya tidak berhenti pada penanganan kasus. Ia harus masuk ke hulu: pendidikan, literasi relasi sehat, pengakuan terhadap kekerasan non-fisik. Jika tidak, negara hanya sibuk memadamkan api, tanpa pernah bertanya mengapa rumah-rumah itu mudah terbakar.
Kekerasan emosional sulit dibuktikan, kata orang. Tapi sulit dibuktikan bukan berarti tidak ada. Justru karena sulit, negara seharusnya lebih serius. Lebih peka. Lebih berani merevisi pendekatan.
Selama ini, korban sering diminta bersabar. Diminta memahami situasi. Diminta menjaga nama baik. Nama baik siapa? Sering kali bukan nama baik korban.
Aurelie menulis karena ia tidak ingin diam diwariskan. Karena ia tahu, luka yang disimpan terlalu lama akan mencari jalannya sendiri—kadang dalam bentuk kehancuran.
Masyarakat kita menyukai cerita yang rapi. Korban yang sempurna. Pelaku yang jelas. Akhir yang tuntas. Padahal kenyataan lebih sering berantakan. Abu-abu. Penuh kontradiksi.
Dari kisah Aurelie, ada beberapa catatan kecil yang layak ditulis di pinggir kesadaran kita.
Pertama, kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan. Kedua, diam bukan selalu tanda setuju—sering kali itu strategi bertahan hidup. Ketiga, pendidikan tanpa empati hanya melahirkan generasi yang pandai menyembunyikan luka. Keempat, negara tidak cukup hanya hadir dalam teks undang-undang; ia harus hidup dalam praktik sehari-hari.
Dan kelima, keberanian satu orang bersuara sering membuka jalan bagi banyak orang lain untuk berkata, pelan tapi tegas: aku tidak sendirian.
Broken Strings bukan hanya kisah Aurelie Moeremans. Ia cermin dari banyak senar yang retak, tapi terus dipaksa berbunyi demi kepuasan sistem.
Pertanyaannya kini kembali ke kita—dan ke negara:
apakah kita akan terus menikmati musiknya, sambil pura-pura tak mendengar suara retaknya? ( AN )
Horas Hubanta Haganupan.
Horas …Horas … Horas
Penulis : Aswan Nasution